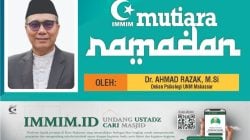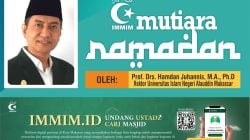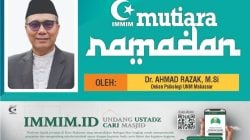Oleh: Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
MAKASSAR, RAKYATSULSEL - “In politics dont see what is happening, but pay attention to the effect” (Dalam politik jangan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi perhatikan efeknya).
Pembuka dari tulisan ini dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa politik yang ada, dan seringkali publik terjebak pada permukaan saja, tetapi kedalaman dalam peristiwa peristiwa politik kian dibungkus dengan apik. Mengapa? Karena dalam politik apa yang nampak namun itu bukan fakta, apa yang diucapkan tetapi bukan itu yang sesungguhnya, dan apa yang diprogramkan namun bukan itu yang dikerjakan.
Seorang novelis Inggris Eric Arthur Blair yang lebih dikenal dengan nama George Orwell dalam esainya yang terkenal Animal farm dan Nineteen Eighty-Four, dan ia berkata “politik itu dirancang untuk berbohong biar terdengar jujur, dan pembunuhan pun didesain agar terlihat terpuji” demikian apiknya soal-soal politik diafirmasi melalui bahasa dan perilaku.
Pada peristiwa politik di Indonesia tahun 2024. Sejumlah partai politik bahkan telah berkoalisi dan memunculkan nama calon pemimpin mereka untuk digadang-gadang sebagai pemimpin ‘ideal’ Indonesia di masa depan. Berbagai upaya dan strategi sudah mulai dilakukan untuk meraih simpati publik demi memenangkan kekuasaan di pertarungan panggung politik nasional. Kompromi demi kompromi dibangun sebagai upaya untuk membangun koalisi dan mitra dalam perhelatan politik.
Mereka saling berlomba-lomba membangun citra diri yang positif untuk mengimpresi publik dengan menampilkan sisi terbaik aktor-aktor politik di berbagai media massa, baik di media arus utama seperti TV dan radio, maupun media berbasis internet atau daring seperti media sosial. Oleh karena itu, perhelatan politik 2024, berbagai media massa, khususnya media sosial bisa dipastikan akan dipenuhi dengan beragam kampanye politik lengkap dengan segala bentuk pencitraan aktor-aktor politiknya.
Model perilaku politik “simulakra” ini semakin mendominasi dengan gaya fantasi, ambisi, dan citra diri terlepas visi misi yang akan dibangun ke depan. Pandangan Baudrillard tentang simulakra ini sesungguhnya mereduksi pikiran politik bahwa tentang idealitas dan realitas politik yang sesunggguhnya. Karena itu perilaku politik kadang tidak menjembatani tentang “apa yang dipikirkan dan apa yang dikerjakan”.
Hal ini tentunya akan memberikan respons yang beragam. Di satu sisi publik mungkin akan dibuat bingung karena aktor-aktor politik tersebut akan secara terus-menerus menampilkan sisi positif mereka, namun di sisi lain ini juga bisa menjadi rujukan untuk menentukan pilihan politik dari citra diri yang mereka tampilkan.
Untuk memahami hal ini, konsep dramatugi milik sosiolog asal Kanada, Erving Goffman, dapat digunakan untuk mencermati citra atau presentasi diri yang dibangun oleh para aktor politik tersebut. Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life (1959) mendefinisikan dramaturgi sebagai sandiwara kehidupan yang mengharuskan manusia memainkan peran dengan menampilkan sisi depan (front stage) dan sisi belakang (backstage). Dalam hal ini, manusia memiliki banyak versi diri dan perannya dalam suatu relasi sosial bersifat sangat cair (fluid) tergantung pada kepentingan yang ingin dicapai.
Sederhananya, konsep ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana individu menampilkan diri dalam interaksi sosial sehari-hari karena apa yang ditampilkan di hadapan khalayak belum tentu sama dengan apa yang tampilkan di ruang dan relasi sosial yang lain. Misalnya, seorang laki-laki yang memiliki profesi sebagai seorang manager harus tampil tegas dan profesional di hadapan karyawannya. Namun ia akan melepaskan atribut dan kualitas tersebut ketika ia berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya.
Di lingkungan kerja pun demikian. Relasi profesional antara atasan dan bawahan juga bisa dipahami dengan konsep ini. Misalnya, seorang pegawai mungkin akan selalu bersikap baik terhadap atasannya meski ia sedang merasa kesal. Hal ini dikarenakan dalam segala bentuk relasi sosial manusia akan menggunakan ‘topeng’ yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan manusia juga memiliki kendali untuk menampilkan dan menyembunyikan yang ia inginkan. Dalam kritik sosial ada adagium seperti ini “bukan orangnya yang berubah, tetapi hanya topengnya yang terbuka”.
Lakon Aktor Politik dalam Dramaturgi
Dalam kaitannya dengan panggung politik, konsep dramaturgi dapat digunakan untuk melihat bagaimana aktor-aktor politik menampilkan dirinya di hadapan publik. Di era digital seperti sekarang, khususnya di media sosial, mereka akan berlomba-lomba mengampanyekan versi terbaik dari dirinya untuk meraih simpati publik.
Citra diri dibangun sedemikian rupa untuk mempengaruhi ruang publik (public sphere), merebut simpatik dalam bentuk poster, pamflet, spanduk, baliho dan alat peraga lainnya. Seperti kalimat monohok dari seorang politikus asal Uni Soviet bernama Nikita Kruschev dia bilang “Politikus semua sama, ingin membangun jembatan, tapi disitu tidak ada sungai” Pandangan ini sesungguhnya mencoba menterjemahkan kalau sebagian nalar politik politikus tidak ber-relasi dengan apa yang ia inginkan.
Tetapi, faktanya mereka akan terus-menerus menonjolkan prestasi, pencapaian, kritik pedas terhadap rival politik, baik di media arus utama maupun media daring, khususnya di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Pemanfaatan media sosial sangat marak di era modern ini karena selain dianggap efektif dari segi pendanaan, cara ini juga memiliki kemampuan mengirim pesan dengan cepat dan bisa menjangkau khalayak di berbagai wilayah. Sepertinya citra diri itu menjadi hal utama di panggung politik dibandingkan dengan nalar politik yang berkolerasi dengan realitas sosial yang ada.
Ludwig Aspling dalam risetnya yang berjudul The Private and The Public In Online Presentations of The Self (2011) mengatakan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai arena pencitraan karena pesan dapat dengan mudah disampaikan secara serentak, tanpa terhalang status sosial. Sehingga politisi cenderung menggunakan jejaring ini sebagai media yang efektif dan murah.
Citra positif yang kerap dibangun di media sosial biasanya adalah sosok figur yang dekat dengan rakyat, nasionalis, tegas, antikorupsi, dan religius. Hal ini sangatlah lumrah karena di media sosial individu memiliki kecenderungan untuk menampilkan sisi positif ketimbang sisi negatif.
Hasil riset Ainal Fitri (2015) melihat bagaimana Prabowo menggunakan platform twitter @Prabowo08 untuk mengelola citra diri positifnya pada Pilpres 2014, 2019, dan 2024 yang lalu. Begitu pula dengan tokoh-tokoh politik lainnya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Mahfud MD, bahkan termasuk selebriti pun menjadikan media sosial sebagai ajang untuk memperkenalkan diri dengan follower yang fantastis.
Hal yang sama juga terjadi dengan Joko Widodo, dan tokoh politik lainnya yang menggunakan media sosial untuk membangun versi terbaik mereka di mata publik. Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan kontestasi politik, mereka akan cenderung hanya akan menampilkan citra diri yang positif saja dan sebisa mungkin menutupi rekam jejak kontroversial atau stigma negatif yang pernah melekat pada dirinya.
Hal yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam dramaturgi citra maupun presentasi diri aktor politik bersifat konstruktif karena memang hal tersebut sengaja dibangun secara konseptual oleh suatu tim besar berdasarkan kepentingan tertentu. Namun, bukan berarti semua bentuk pencitraan adalah hal yang bersifat buruk dan manipulatif sehingga kita menjadi pesimistis dan kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap tokoh-tokoh yang dicitrakan.
Meskipun bersifat konstruktif dan konseptual, tidak semua bentuk citra diri itu negatif. Sejak dulu hingga era digital saat ini, role model atau figur yang representatif sangat diperlukan dan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari citra diri dalam konsep dramaturgi. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap ‘baik’ juga perlu dicitrakan dan dikampanyekan karena jika tidak hal tersebut akan terabaikan oleh publik dan fatalnya bisa dikalahkan dengan bentuk-bentuk citra diri yang lain.
Oleh karena itu, untuk menanggapi hal ini, kemampuan diri kita dalam menilai tokoh politik sangat diperlukan. Artiny, kita sebagai individu harus meningkatkan literasi politik, mampu mengedepankan budaya berpikir kritis-analitik dalam menilai sesuatu supaya tidak mudah terbuai dengan citra diri di permukaan dan lebih cerdas dalam berdemokrasi.
Selain itu, budaya mengecek fakta (fact-checking) juga sangat penting untuk mengenal calon pemimpin serta melihat rekam jejak positif maupun negatif yang dimilikinya supaya kita lebih ‘matang’ dalam menentukan pilihan politik kita.
Dramaturgi dalam demokrasi dan itu terus menerus terjadi, citra diri seorang pemimpin selalu dibangun dari pola-pola yang klasik seperti kesederhanaan, populis, merakyat, karena hal seperti ini memudahkan memberi pengaruh pada publik.
Walau pada akhirnya peran para dramaturgis itu hanya lakon di panggung depan yang penuh kamuflase, tetapi wujud aslinya sesungguhnya ada di panggung belakang yang penuh kompromi, konspirasi, bahkan (bisa) juga skandal dan kejahatan dilakoni.
Dan, ini inilah lakon dramaturgi demokrasi. (*)